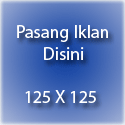Bagaimana film bisu tumbuh dan hilang di
negeri kita?
THE Artist menjadi film bisu pertama yang meraih
Oscar film terbaik sejak penyelenggaraan Oscar pertama, 84 tahun lalu,
memenangkan film bisu, Wings (1928).
Menarik bagaimana film bisu bisa mencuri
perhatian masyarakat kontemporer yang sudah ramah dengan sinema 3D.
Banyak yang menganggap The Artist adalah sebuah surat cinta pada era
film bisu.
Di tengah hangatnya pembicaraan soal The Artist
rasanya pas bila kita menengok perkembangan film bisu di tanah air.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negeri kita yang waktu itu masih
bernama Hindia Belanda tak ketinggalan dengan perkembangan teknologi
baru bernama: sinema.
Hanya berselang 5 tahun setelah Lumiere
Bersaudara mempertunjukkan film pertama kalinya di Paris, Perancis,
masyarakat Batavia (nama Jakarta ketika itu) pada Desember 1900 sudah
menikmati pertunjukan film. Waktu itu, di Tanah Abang Kebon Jahe
(Manage), warga Batavia nonton gambar idoep “Sri Baginda Maharatu
Belanda bersama Pangeran Hertog Hendrick memasuki ibukota negeri
Belanda, Den Haag.”
Pada tahun-tahun permulaan ini, bioskop belum
punya tempat tetap. Pemutaran berpindah-pindah dari satu tempat ke
tempat lain, seperti menyewa gedung milik Kapten Cina Tan Boen Koei.
Yang sederhana diputar di lapangan terbuka seperti di lapangan Mangga
Besar atau di los pasar Tanah Abang. Pertunjukan di alam terbuka
karcisnya biasanya lebih murah. Bagus jeleknya proyektor film juga
menentukan harga karcis. Tempat duduk pria dan wanita dipisah.
Seiring waktu, mulai ada pengusaha yang masuk
bisnis bioskop. Selain bioskop keliling juga ada gedung yang khusus
memutar film. Sesudah film punya gedung permanen, muncul bioskop sesuai
kelas ekonomi dan status masyarakat yang beda-beda. Di setiap kota
besar, ada bioskop yang khusus bagi kalangan Eropa saja. Di Jakarta ada
bioskop Deca Park, di Bandung ada di Gedung Concordia. Di Jakarta juga,
di seberang masjid Istiqlal sekarang ada bioskop Capitol yang merupakan
bioskop kelas satu. Selain itu, di Pasar Senen, ada bioskop Kramat
Theater yang merupakan bioskop kelas 2. Lalu ada juga bioskop kelas 3
bernama Rialto di Pasar Senen.Untuk orang kelas bawah, lebih asyik
nonton film ke bioskop kelas 3, karena mereka tak perlu jaim (jaga
image).
Seiring waktu pula, tontonan yang ada bukan hanya
film dokumentasi. Tapi juga film cerita. Semuanya film bisu alias tak
bicara. Di majalah Intisari tahun 1977, wartawan sekaligus sineas era
sebelum kemerdekaan Tanu TRH bercerita di bagian utara Kota,
benedenstad, di kalangan kelas bawah, kebanyakan diputar film-film
action terutama film-film western (cowboy). Sedang di bioskop kalangan
atas, di wilayah selatan kota, bovenstad, lebih disukai film drama.
Aktor kesayangan penonton yang suka film action
masa itu adalah Eddie Polo, Tom Mix, Harry Cabot, dan Hoot Gibson. Eddie
Polo di masyarakat sini digelari Si Mata Banteng. Eddie Polo juga
disebut sebagai “Raja dari segala jago seri”.
Seri? Maksudnya? Ah, ini dia. Film-film action
itu berseri. Lebih tepatnya lagi, menurut ukuran zaman kiwari tergolong
film pendek. Film-film Eddie Polo juga tak diedarkan, atau tepatnya
diiklan dengan judul Inggris. Judulnya dialih-bahasakan biar bisa
diterima masyarakat luas. Umpamanya, film Rasia Ampat yang diputar
September 1923 menyajikan seri ke-23 dan 24. Mengecek situs imdb yang
dimaksud seri jagoan Eddie Polo mungkin saat yang bersangkutan memainkan
karakter Cyclone Smith sampai berkali-kali dalam serangkaian film
pendek.
Seperti ditulis Misbach Yusa Biran di buku Bikin
Film di Jawa 1900-1950 (terbit 2009), importir film masa itu tak mau
bikin pusing pelanggannya dengan memberi judul asli berbahasa asing.
Cukup beri judul yang menarik, orang pasti datang. Untuk film action
berisi perkelahian diberi judul Oedjan Djotosan. Film yang banyak berisi
kejar-kejaran mobil diberi judul Adoe Mobil. Ada juga film yang tidak
mengandung action, diberi judul Ditoeloeng Singa, tapi hanya bertahan
sehari karena bioskop sepi.
Selain film Barat, masyarakat Batavia, terutama
yang tinggal di daerah pecinan, juga akrab dengan film-film dari negeri
Tiongkok. Pada 1923 di Batavia sudah ada importir film Cina. Di buku
yang ditulis Misbach dicontohkan iklan importir film Cina yang
mewartakan sudah menerima rupa-rupa film-film yang diimpornya dari
Tiongkok. Film-film Tiongkok itu “ada memberi pemandangan keloetjoean
dan keheranan jang ada dimaenkan oleh acteur totok jang sudah terkenal.”
Ia menyebut judul-judul film yang diimpornya dalam bahasa Melayu:
“Akalnja Satoe Tukang Kajoe akan Mendapatkan Isteri”, “Oepahnja Anak
jang Berbakti”, ‘Charlie Chaplin Tiongkok”, “Pemandangan Indah di Gunung
Tai San”, “Mantoe yang Terseksa”. Apa judul-judul asli film-film itu
tak diketahui.
Tak hanya jadi penonton, kita juga lantas membuat
film.
Film cerita pertama yang dibuat di Hindia Belanda adalah Loetoeng
Kasaroeng tahun 1926. Pembuatnya masih orang asing (L. Heuveldorp dan
G. Krugers). Dicatat di buku Katalog Film yang ditulis JB Kristanto,
walau pembuatnya orang asing, ini film cerita pertama di Indonesia yang
menampilkan cerita asli Indonesia. Duo Heuveldorp dan Krugers masih
membuat film setahun kemudian, Euis Atjih. Pada 1928, Wong Bersaudara
menyelesaikan pekerjaan film yang semula dibuat sineas Amerika, Len H.
Ross. Filmnya berjudul Lily van Java (1928). Pembuat filmnya
memproklamirkan perusahaan film mereka sebagai “kongsie pembikinan film
pertama di Indonesia.”
Sampai tahun 1930 film yang dibuat di tanah air
bisu. Film suara dibuat G. Krugers pada 1931 berjudul Atma De Vischer.
Selain Krugers, sineas yang juga membuat film suara dengan alat
percobaan seadanya adalah The Teng Chun lewat filmnya Boenga Roos dari
Tjikembang (1931). Pengerjaan film dilakukannya seorang diri. Ia juru
kamera, sutradara, penulis, dan lain sebagainya. Alat perekam suara yang
digunakan pun hasil otak-atik sendiri.
Hasilnya kurang memuaskan. Karena suaranya buruk,
film ini dikritik habis oleh kritikus film/wartawan masa itu Andjar
Asmara di koran Tjahaja Timoer. Menurut Teng Chun, seperti dikutip
Misbach, kegagalan filmnya karena suaranya buruk dan sangat berisik.
Tapi ia tidak ambruk oleh kegagalannya. Teng Chun
kemudian membuktikan jadi pengusaha film yang berhasil hingga Jepang
datang. Misbach mencatat, faktor penting film Teng Chun adalah kelahiran
“film bicara”. Era film bisu tamat di tahun itu.***
(ade/ade)
sumber
sumber